
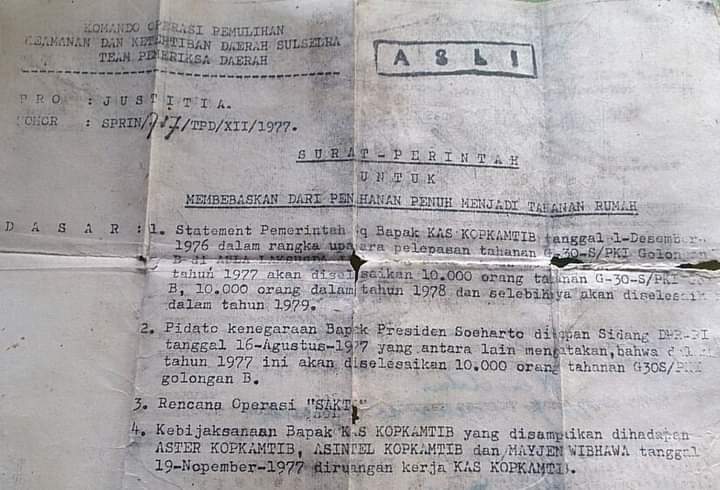
Inilah Nanga-Nanga. Kampung di kecamatan Baruga kota Kendari Sulawesi Tenggara. Kampung ini dibuka tahun 1978 oleh 37 keluarga bekas tahanan politik peristiwa 1965. Mereka dilepas setelah dijeblos ke tahanan, tanpa surat penangkapan tanpa pengadilan. kampung Nanga-Nanga hanya berjarak 20 kilometer dari ibukota Sulawesi Tenggara, Kendari.
Saat ini hanya ada 20 rumah disana. sebagian besar masih berbentuk asli seperti ketika dibangun dua puluh tujuh tahun silam. Rumah berdinding papan dicat putih beratap seng campur rumbia dengan satu jendela di bagian depan. Sebuah mesjid dan sebuah gereja, serta puskesmas pembantu dibangun di sana. Bila siang kampung sepi seperti kosong penghuni. Orang-orang masuk ke hutan mencari dolken sejenis kayu anakan penyangga bangunan. Dolken yang mereka cari bakal dihargai 500 rupiah per batang. Tapi dengan cara itu mereka hidup.
Di Sulawesi Tenggara, penangkapan pertama terjadi pada 18 Oktober 1965. Delapan pimpinan PKI di tahan Korem 143. Disusul tindakan lain berbau kebencian yang menyebar secara cepat di propinsi ini dan menulari daerah-daerah kabupaten lain. Pada tahun 1968, 200 orang yang dikategorikan bagian dari Partai Komunis masuk tahanan.
“Saya tak bisa tidur mendengar semua itu. Terlebih lagi karena Buton disebut sebut sebagai pemasok senjata bagi Partai Komunis,” Lambatu, salah seorang eks Tapol PKI.
Wa Ode Zatimah, istri Lambatu meriang sejak penyisiran anggota partai dilakukan. Kata Lambatu, Ia tak pernah memikirkan hidupnya akan berubah, Ia hanya mengira dirinya akan diinterogasi (bila penangkapan dilakukan), setelah itu Ia bisa meneruskan hidupnya kembali. Ia menenangkan istrinya dan mengatakan musuh partai komunis hanyalah imperialisme dan feodalis, yang lainnya tak ada. Tapi Ia salah. Pada 7 November 1965, sejumlah anggota pasukan masuk ke rumahnya. Istrinya berdiri gemetar. Anggota pasukan militer itu mencari dokumen yang terkait dengan kudeta jenderal. Ia di gelandang ke kantor militer malam itu, mengalami penyiksaan fisik dengan interogasi berhari-hari, berbulan-bulan dengan pertanyaan sama hingga Ia tak bisa berpikir. Mengapa masuk PKI? Mana dokumen-dokumennya? Struktur PKI seperti apa? dan pertanyaan lain yang membuatnya tercengang-cengang.
Keluarganya ikut diinterogasi. Zatimah mendapat giliran pertama. Perempuan ini menangis dan mengatakan hanya tahu kalau suaminya ikut rapat. Dari anggota tahanan lain, Lambatu tahu istrinya mendapatkan kekerasans seksual selama diinterogasi. Ia menangis karena tak mampu melakukan apapun untuk menolong istrinya. “Hidup seperti apa ini…”
Ia tak bisa lagi berpikir. “Saya hanya ingin ini segera berakhir. Jangan sakiti istri dan keluarga saya lainnya.”
Ia lalu mengamini bahwa benar ada rapat untuk kudeta. Ia bermohon-mohon keluarganya tak lagi di ganggu. Ia dipindahkan ke sel Buton pada tahun 1970. Tak seorangpun pernah menjenguknya, melakukan hal ini sama halnya memindahkan penyakit ke tubuh orang sehat. Di luar tahanan, istrinya meninggal dengan jiwa terganggu. Ia pergi dengan label PKI dan karena memiliki suami yang bertekad ingin mengubah wajah negeri ini. Bupati Buton, Kasim, yang dikategorikan terlibat dalam keanggotaan Partai Komunis dinyatakan bunuh diri dengan cara menggantung diri di tahanannya. Hingga bertahun-tahun berikutnya, istrinya terus meminta penjelasan benar tidaknya bunuh diri ini. Berita melegakan tiba di tahun 1969, ketika Pangdam Wirabuana Andi Azis Rustam dan Oditur Militer Kol Busono dan Kol Bagyo dari Direktorat Kehakiman Pusat berkata, Buton tak terbukti menjadi wilayah pemasok senjata dari China. Tapi terlambat sudah. Jiwa-jiwa itu telah pergi dengan kekerasan yang dibenamkan dalam tubuh dan pikiran mereka. ***
Tahun 1977, Lambatu menjalani hari-hari yang disebut ‘dimanusiakan kembali’. Bersama 42 orang lainnya Ia menempati lokasi terkosentrasi Nangananga. Wilayah seluas 84 hektar ini dikapling-kapling dan dirancang terpusat agar mantan tahanan politik ini mudah dimonitoring. Ratusan orang tiba lebih awal disini. Ia mendengar kabar ratusan orang lainnya telah tewas dalam kerja-kerja paksa pembukaan lahan hutan, transmigrasi, jalan-jalan di bawah kontrol militer di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara. Pikiran Lambatu tak lagi jernih, meski Ia tak mati, namun Ia tak punya bayangan seperti apa hari esok.
Ia mengusir sedihnya dengan mengurusi kebun di belakang rumahnya. Kebun yang tak bisa berkembang. Di tahun pertama menetap di Nangananga Ia tak punya nyali bertemu orang lain di luar Nangananga. Ia merasa ada cap PKI di tempeli di kepalanya. Meski Ia tak mengatakan itu, namun ketika orang tahu Ia berasal dari Nangananga, identitas sebagai eks tahanan politik terkuak. Tahun-tahun berikutnya, Ia mencoba berhenti mengenang kejadian buruk di masa lalunya. Tapi ia begitu kesepian, hingga tak mudah beranjak dari kenangan-kenangan tersebut.
Yanasin, eks tahanan politik lainnya menjual tanah depan rumahnya, Ia lalu menyingkir ke rumah kecil belakang tanahnya. Mencoba berdamai dengan hidupnya.. “Saat kami berkunjung, mereka tak tahan untuk tidak bergembira seperti anak kecil. Tamu adalah hal luarbiasa dalam hidup mereka. Menerima orang luar seperti membangunkan kembali rasa percaya diri yang hilang,”ujarnya.
Lambatu selalu menerima tamu dengan sikap gentle. Ia berpakaian rapi, kemeja dimasukkan dalam celana katunnya dan Ia berdiri depan pintu hingga tamu-tamu itu muncul. Ia selalu mengingatkan membawa buku, suratkabar, apapun untuk bisa dibaca-baca membunuh sepi. Ia telah melewati sesuatu di masa lalu, somewhere in time, yang begitu pahit untuk di panggil sebagai memori. Tapi kini pembunuhan lain mengintip mereka ; kesepian dan tersisihkan.
Hari ini di Nanga-nanga hanya 37 keluarga. Mereka merupakan anak dan cucu generasi kedua dan ketiga dari para bekas pengurus dan angggota PKI, hanya tersisa 6 orang bekas tapol PKI yang masih hidup di kampung Nanga-Nanga. Mereka adalah La Mbatu, La Une,Sutami, Maho, Yanasin dan
Zakaria. Sedangkan yang lainnya terpaksa meninggalkan kampung Nanga-Nanga, karena tak tahan hidup di tengah hutan, dan sebagian lagi meninggal dunia.
La Mbatu, La Une, Sutami dan Maho adalah mantan tapol PKI dari kabupaten Buton, Muna dan Kendari. Sementara, Yanasin dan Zakaria dari Sulawesi Selatan. Sebelum terlibat dalam partai komunis, mereka adalah kepala sekolah, guru dan pegawai negeri sipil.
La Mbatu berusia 70an tahun. Ia masih tampak sehat. Sebelum masuk partai, ia bekerja di perpustakaan
negara Makkasar tahun 1956. Di sanalah La Mbatu mengenal berbagai jenis buku-buku kiri dan membaca semua buku karya lenin, marxisme serta tertarik dengan partai komunis yang menawarkan program lebih baik dibanding partai lain yang katanya kapitalis. La Mbatu mengidolakan buku negara dan revolusi karya Lenin.
Tahun 1964, ia kembali ke Buton Sulawesi Tenggara dan menjadi guru SMP. Pada saat yang sama, partai komunis menarik simpatinya. Ia tidak keberatan ketika ditawari menjadi sekretaris comite sub seksi CSS partai komunis, kecamatan Kapontori kabupaten Buton. Ia mengingat, ketika itu, kegiatan partainya lebih banyak berdiskusi antar simpatisan dan kader PKI tentang, bagaimana memajukan daerah. Karena menurut dia, partai komunis tergolong partai baru di daerah itu.
Menurut La Mbatu,kondisi politik lokal Buton masih menyisakan feodalisme kerajaan. Untuk itu, harus diubah secara perlahan dengan mendirikan partai komunis. Ia masih berusia 30 tahun saat itu dan sangat bersemangat. Partai komunis merupakan partai pertama di Sulawesi Tenggara yang memiliki pengurus di tingkat provinsi atau dinamakan CDB. Pengurus di tingkat Provinsi juga terlibat dalam pemebentukan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketika itu, partai komunis sudah mulai menjalankan roda organisasinya dengan membentuk pengurus sampai tingkat kecamatan.
” politik buton terjadi dua kontradiksi. Buton itu kan sisa-sisa kerajaan,pusat kerajaan
disana. Di sinilah yang bertugas di desa ¬desa itu mau menanamkan sisa -2 dulu itu.inilah yang perlu kita
tantang. Ndak kita menggalang front yang baik kerja baik.dalam pros nasakom itu kerja baik,utuh.itu yang kita herankan. Heran, kenapa sesuatu kejadian tidak sama sekali kita cium,kita tau.padahal semuanya satu.yang dimana nasakom itu satu,” tuturnya.
Namun siapa sangka bahwa itulah awal mula kepahitan hidupnya dimulai? Diawali kabar yang didengarnya dari radio transistor milik tetangga, bahwa para jenderal di Jakarta telah diculik dan akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Peristiwa itu, dikenal dengan sebutan gerakan 30 September 1965.
” ndak ada. sama sekali tidak ada berita. Itu mi yang kita herankan. kemudian rencana partai ,tidak
ada istilah kup dari partai. sebab partai tidak ada yang dihianati. hanya yang di hianati adalah
musuh-musuh imprealis, feodalis. Itulah musuh-musuhnya,” ungkap Lambatu.
Situasi mulai tidak menyenangkan. Nama partai komunis disebut-sebut sebagai dalang peristiwa tersebut. La Mbatu mulai merasa sangat khawatir ketika partai komunis dinyatakan sebagai dalang gerakan 30 september dan pemerintah mengumumkan PKI sebagai partai terlarang. Pada pukul 7 malam di bulan November tahun 1965, di kecamatan kapontori beberapa petugas kepolisian langsung menangkap dan menggeledah
rumahnya untuk mencari dokumen apapun yang terkait dengan peristiwa kudeta para jenderal. Ia dijebloskan ke penjara Buton hingga tahun 1970 tanpa surat penahanan dan pengadilan.
Ia mengingat, interogasi dilakukan berulang-ulang dari tahun ke tahun, dari pagi hingga tengah malam
dengan pertanyaan yang sama. Seperti kenapa terlibat PKI,anda tahu PKI Partai terlarang?
” Dengan penyiksaan dipukul.sehingga banyak korban. Ikut di pukul. Keluarga.
Saya punya keluarga turut jadi korban. Meskipun mereka di luar. Karena pemaksaan ini dalam mencari
dokumen-dokumen. Sehingga diadakan penggeledahan di dalam rumah. Dalam penggeledahan itu terjadi pelanggaran seksual dari petugas pada waktu itu. Oleh Anggota koramil. Terhadap istri saya. Saya terus terang,” ceritanya.
Akibat kejadian itu, istrinya stres, hingga meninggal dunia di tahun 1976. Saat itu, ia belum memiliki anak. Untuk mengetahui siapa yang salah dan benar dalam peristiwa itu, menurut La Mbatu, pemerintah harus menegakkan Hak azasi manusia dan perlunya pelurusan sejarah.
Penangkapan itu, bukan saja menjadi kenangan gelap yang senantiasa melintas dalam hidup mantan tahanan politik itu, tapi juga menjadi catatan buruk bagi para anak cucu mereka yang ikut menderita dan disisihkan dari pergaulan selama berpuluh-puluh tahun. Ini dirasakan oleh Ambardin. Dimana bapaknya La Ode Hadidi terlibat dalam partai komunis, saat menjadi kepala mantri kesehatan Se-wakatobi.
Ambardin mengenang, saat bapaknya ditangkap, ia baru berumur 2 tahun. Ia tidak tau situasi saat itu, tapi setelah masuk sekolah dasar baru ia mengerti. Di sekolah ia di kucilkan dan tidak bisa bergaul dengan anak-anak lain yang orang tuanya tidak terlibat dalam partai komunis.
” seperti anaknya angkatan darat, tentara. Kalau ingin dia mau pukul kita, tidak segan-segan
mereka. Asal dia melihat itu, eh anaknya PKI itu, langsung dia buru kita. Seperti keluarga dekat itu banyak yang sudah tidak mengakui lagi, bahwa itu keluarga saya. Apa lagi dia sebagai PNS, polisi dan
tentara itu sangat takut sekali.
Akibat stigma itu,ia tidak mempunyai cita-cita lagi.Karena pemerintah melarang anak-anak PKI untuk
menjadi PNS dan pekerjaan lainya.Bahkan mereka tidak apat mengurus kartu tanda penduduk. Ia lalui
masa-masa sulit itu sejak bapaknya di penjara. Dia bersama ibu dan saudara-saudaranya terpaksa harus
menahan lapar dan hanya minum air seharian.Karena untuk mendapatkan makanan saat itu sangat susah. Sementara keluarga dan masyarakat menjauhi mereka.Mereka di isolir oleh masyarakat sekitar.
Kepahitan yang sama di rasakan La Une, salah seorang mantan Tapol PKI dari Kabupaten Raha. Ia ditahan tahun 1966. Berbagai penyiksaan dirasakannya. Bagian kepalanya dipukul hingga pingsan. Penganiayaan yang lebih sadis adalah alat vitalnya di Setrum. Peristiwa ini tidak dialami La Une sendiri, tapi juga beberapa tapol di Buton. Penyiksaan itu berbuntut hingga ke pembagian jatah makanan. Tiap tapol diberi 50 bulir jagung sebagai makanan sehari. Akibatnya banyak yang kelaparan dan akhirnya meninggal dunia. Setiap harinya, mereka di interogasi dengan berbagai macam pertanyaan seputar senjata dan dokumen tentang rencana pengkudetaan. Kata La Une dirinya di paksa untuk mengakui semua pertanyaan tentang pasokan senjata dari Jawa ke Buton, terkait rencana pengkudetaan. Jika menjawab tidak tahu, ia di pukul hingga babak belur. Beberapa rekannya bahkan tewas akibat pukulan tersebut.
” Kalau terbukti memang saya terlibat dalam senjata ini, saya rela dihukum mati.di bunuh di
tempat.saya tanda tangan dengan darah saya sendiri dari pada siksa. Sebab kalau saya kan di buton itu kasian hancur-ran. Karena ada satu yang mengaku terpaksa terlibat semua itu senjata. Akhirnya kasian yang tidak tau menahu bertahan ya mati. tuduhan tuduhan .ternyata tidak terbukti. didatangkan dari surabaya dan jakarta, tidak ada itu senjata di Sulawesi Tenggara. Alhasil teman-teman banyak yang jadi korban,” katanya sedih.
La une mengatakan, ia juga ditanyai tentang adanya keterlibatan 17 pejabat daerah Kabupaten Muna dalam Partai Komunis. Padahal ia tahu semua pertanyaan yang dilontarkan petugas hanya jebakan saja. Agar para pejabat daerah yang dianggap dekat dengan orang PKI, ditangkap dan di anggap juga anggota PKI.
Penyiksaan itu mulai berkurang pada tahun 1970. Mereka dinyatakan bebas namun masih tetap harus menjalani masa isolasi di tempat lain. Pada malam hari tahun 1970, dengan menggunakan kapal laut bernama Sultra, La Une dan puluhan eks tapol dari Muna diangkut ke Kendari. Mata di tutupi kain. Ini dimaksud, agar para eks tapol tidak tahu lokasi tujuan mereka selanjutnya. Tibanya di kendari pada pagi hari, mereka digiring ke kamp pengasingan di Ameroro Kabupaten konawe. La Une mengaku dilarang bertemu dengan istri maupun anaknya. Saat itu,Ia hanya berbekal dua potong pakaian dan tikar menuju ke kendari.
” ini yang paling saya rasakan sampai hari ini. Begitu istri saya mendengarkan bahwa katanya mereka sudah di bawa ke kendari, dia kejar sampai ke pelabuhan. ini sedih sekali,dia bawa anak-anak semua. Di pelabuhan tidak boleh ketemu mereka. Kita sudah cepat turun di kapal. Saya bilang, kayak betul-betul golongan anjing mungkin mau di tembak ini.Biar ketemu sebentar dengan keluarga, katanya kalau bisa pak, saya mau ganti tempat tidurnya.tempat tidurku saya ambil di lembaga,saya bawa di sini. Dia bilang istriku ada yang baru, tidak bisa ketemu,” imbuhnya.
Selama di kamp pengasingan Ameroro, mereka juga mengalami penyiksaan. Tapi tidak separah seperti di penjara Buton ataupun Muna. Lagi-lagi keluarga, tidak bisa menemui mereka.
Di pengasingan itulah La Une bertemu dengan eks tapol yang berasal dari Buton, kendari dan Makkasar yang kini menjadi karibnya. Ia bertemu Yanasin. Mantan Tapol PKI dari Makkasar.
Yanasin berasal dari Banggai Sulawesi Tengah. Ketika di Makassar, ia tinggal bersama omnya yang juga teman dekat Kahar Muzakar Tokoh pergerakan DI TII. Pada tahun 1954 , Yanasin bekerja sebagai staf karyawan jawatan kesejahteraan angkatan darat. Setelah itu,ia ikut dalam berbagai kegiatan PKI, seperti diskusi-diskusi tentang perkembangan bangsa dan bagaimana memperjuangkan kepentingan buruh. Saat penangkapan, dia berada di rumah salah seorang pengurus penting PKI di Makkasar bernama Ali. Karena pemilik rumah tak ditemukan, akhirnya tanpa surat penahanan dan proses pengadilan, Yanasin langsung di bawa ke kodim. Setelah itu pindah-pindah penjara seperti dari penjara Makkasar di Karebosi, ke penjara Maros, dan terakhir di rumah tahanan militer atau RTM. Oleh pemerintah saat itu dia di masukkan dalam golongan B atau golongan berat di parti komunis. Di penjara karebosi ia menempati sel ukuran kecil dan hanya sendiri. Inilah cerita Yanasin.
” Hanya satu tempat tidur. Dan di situ ditulis tidak boleh bicara dengan orang tahanan ini.
Jadi orang semua takut. Biarpun ada orang rupanya kasian, prihatin, kalau pulang itu liat babak belur, ndak berani dekat-dekat karena itu ada tulisan, takut. Sedangkan pelayan sendiri, itukan pintunya bekas pemberontak di penjara itu.Jadi pintunya double besi. Jadi kebetulan saya kebetulan di berikan pelayan orang bisu,orang bisu yang ditahan. Saya di sel trus,jadi saya tidak bisa gambarkan,” jelasnya.
Yanasin telah kehilangan istri akibat penyakit kanker payudara. Pada saat yang sama ,ia
juga menderita pembengkakan jantung. Ketika istrinya meninggal, ia mengaku sudah tidak bisa menangis lagi. Hidupnya telah penuh dengan kesakitan dan memasuki tahap ambang batas yang melelahkan. Katanya, mungkin beginilah hidup. Tak bisa dibayangkan akhirnya. Terjadi begitu saja dan tiba-tiba semuanya hilang, termasuk kemerdekaan.
Naskah & Foto : Kiki











